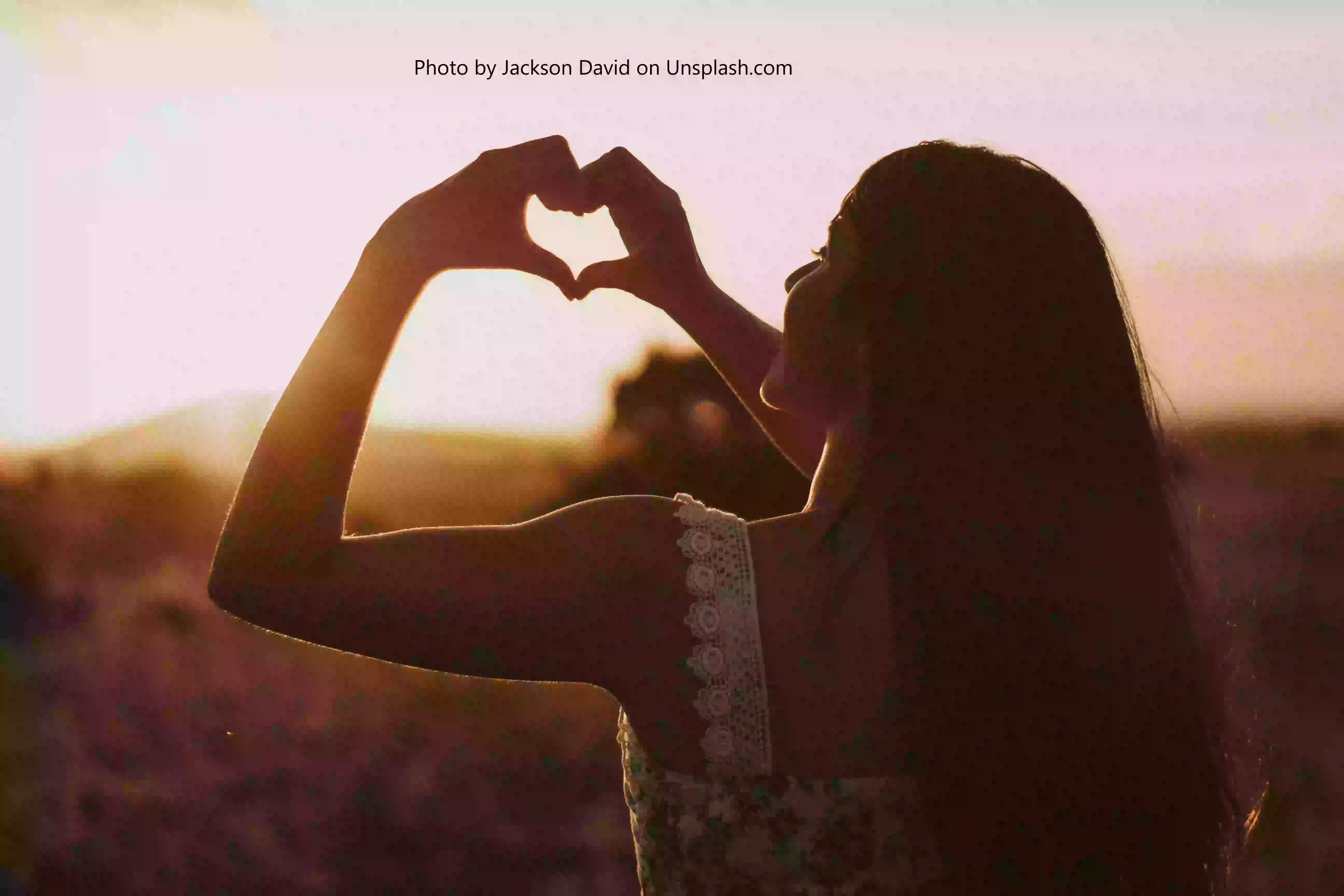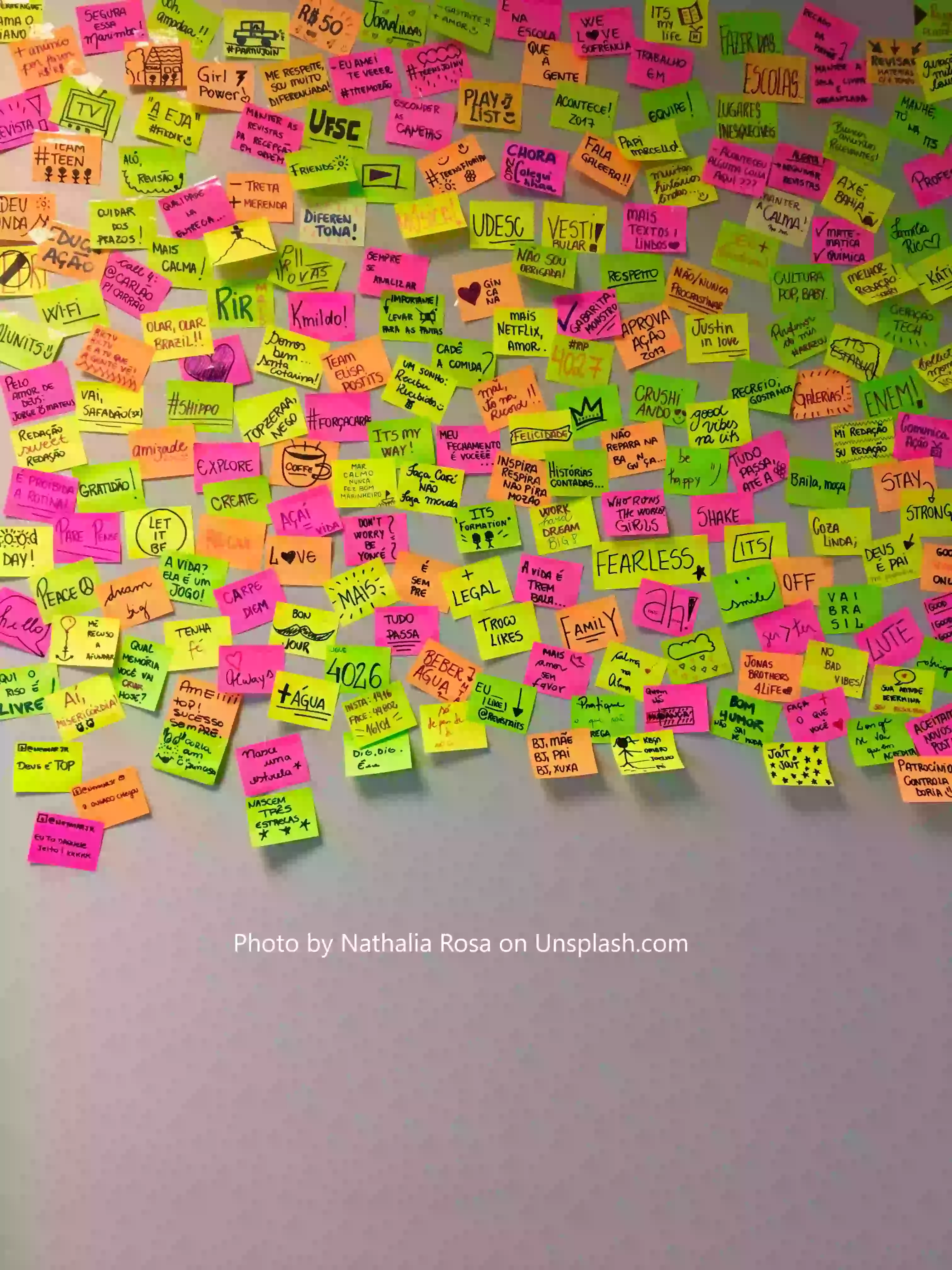Tindakan atau pemikiran untuk bunuh diri memiliki latar belakang yang kompleks dan berbeda-beda antar individu. Interaksi antara faktor genetik, ada tidaknya adiksi atau trauma, hadirnya stresor luar biasa, kemampuan manajemen stres, keterampilan dan dukungan sosial, atau cara pandang budaya turut memberi andil dalam terbentuknya niat untuk bunuh diri. Persebaran kasus bunuh diripun bisa ditemukan di berbagai kelompok masyarakat, baik golongan sosial ekonomi rendah, menengah, atau tinggi, di berbagai kelompok etnis atau agama, dan dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang pendidikan.
Berbagai penelitian psikologi dan psikiatri kini memungkinkan kita untuk mengetahui apa saja kondisi yang umum mengawali munculnya perilaku bunuh diri. Thomas Joiner menganalisis dan merangkumnya dalam bukunya Why People Die by Suicide. Joiner (2005) menyatakan bahwa kemampuan untuk menyakiti diri sendiri secara serius adalah faktor terpenting yang berkaitan dengan tindakan bunuh diri. Secara biologis, manusia sebenarnya dikondisikan secara alami untuk menjaga nyawa dan eksistensinya. Berbagai perubahan dalam proses evolusi bahkan terjadi untuk mendukung manusia bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu kemampuan untuk melukai diri berakar dari kebiasaan yang dipelajari individu selama hidupnya dan tidak terberi secara biologis. Tidak adanya rasa takut, toleransi yang tinggi terhadap rasa sakit, dan pemahaman bagaimana melakukan perilaku yang beresiko membuka peluang lebih tinggi terjadinya tindakan menyakiti diri sendiri yang dapat berujung pada bunuh diri.
Di samping itu Joiner (2005) menyatakan keinginan untuk bunuh diri kerap muncul saat manusia menganggap dirinya tidak dapat memenuhi dua kebutuhan mendasar sebagai makhluk sosial. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk memberi sumbangsih kepada kelompok. Individu yang berpikir untuk bunuh diri cenderung mempersepsi bahwa ia tidak kompeten dan kondisi ini membuatnya merasa menjadi beban (burdensome) bagi kelompoknya, misalnya anak yang merasa tidak mampu memenuhi tuntutan keluarga atau orang lanjut usia yang malu harus bergantung dengan pendampingan orang lain. Individu dalam kondisi ini menganggap bahwa situasi yang dihadapinya tidak dapat diubah dan hanya dapat diselesaikan dengan kematian.
Kebutuhan kedua adalah kebutuhan akan koneksi atau hubungan dengan orang lain. Manusia memang hampir selalu berinteraksi dengan sesama dan berada bersama dalam suatu kelompok, namun hal ini tidaklah cukup. Individu membutuhkan rasa memiliki dalam sebuah relasi interpersonal dan mengidentifikasi diri dengan satu kelompok tertentu (belongingness). Kondisi ini dapat cenderung sulit untuk dicapai bila individu memiliki kesulitan membangun rasa percaya dalam hubungan interpersonal, misalnya akibat trauma di masa kanak-kanak. Penolakan juga dapat dirasakan individu saat ia dianggap bukan menjadi bagian di kelompok yang ia tuju, misalnya karena memiliki kondisi fisik, cara pandang, kemampuan, atau status sosial yang berbeda. Isolasi dan penolakan sosial dapat mengakibatkan stres dan menimbulkan rasa sakit yang bahkan dirasakan sama nyatanya seperti sakit secara fisik. Masalah dalam relasi interpersonal seringkali menjadi pemicu munculnya niat bunuh diri.
Tindakan bunuh diri jarang terjadi begitu saja. Berdasarkan prakteknya di klinik psikiatri di Swiss, Thomas Reisch (2012) menyatakan bahwa secara umum tindakan bunuh diri berlangsung dalam enam tahapan. Model tahapan yang diajukan oleh Reisch memang tidak bisa digeneralisasikan untuk semua kasus bunuh diri. Meskipun begitu, pengetahuan tentang kondisi individu di tiap tahapan memberi peluang untuk melakukan pencegahan bunuh diri yang lebih efektif, sesuai kebutuhan individu di tiap tahapan. Pencegahan bunuh diri yang tepat dapat membuka peluang individu tidak melangkah ke tahapan yang lebih lanjut.
Tahapan pertama disebut sebagai fase pra-bunuh diri (Präsuizidale Phase). Di tahap ini individu menunjukkan gangguan kesehatan mental. Bisa jadi individu memang menerima diagnosis klinis, misalnya gangguan depresi. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan individu hanya menunjukkan simtom-simtom tertentu, namun tidak cukup untuk menegakkan diagnosis klinis, misalnya gangguan psikosomatis, menarik diri dari interaksi sosial, tidak lagi menunjukkan minat terhadap hal-hal yang dulunya menarik baginya, dan sebagainya. Kondisi psikis individu di tahap ini lemah dan cenderung lebih sulit baginya melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Di tahap ini terapi oleh psikolog dan psikiater dapat mencegah munculnya kondisi yang lebih parah. Di samping itu, penting pula untuk melibatkan dokter umum untuk mengidentifikasi, apakah masalah yang dialami individu adalah memang masalah kesehatan fisik atau justru disebabkan tekanan psikis yang berlebih. Dokter umum dapat selanjutnya merujuk individu untuk mendapatkan penanganan psikologis.
Di tahapan kedua, yang disebut sebagai Mental-Pain-Phase atau fase sakit secara mental, individu mengalami krisis emosional akibat stresor dari luar diri. Di fase ini sangat sulit bagi individu untuk mengingat hal positif di masa lalunya sekaligus menunjukkan antusiasme terhadap pengalaman positif di masa depan, misalnya rencana liburan atau datangnya hari raya. Selain itu sulit bagi individu untuk berpikir secara rasional dan menunjukkan rasa tanggung jawab atau kepedulian akan lingkungan sosialnya, misalnya dari mana keluarganya akan mendapat penghasilan bila ia meninggal. Fokus individu di tahap ini adalah menghilangkan rasa sakitnya, namun sayangnya individu sulit melakukannya secara rasional. Di tahap ini individu membutuhkan penanganan krisis yang intensif secara medis. Individu juga sebaiknya dijauhkan dari benda-benda yang bisa membahayakannya. Konsumsi media di tahap ini sebaiknya juga sangat dibatasi untuk mengurangi kemungkinan individu membaca berita yang memicu reaksi emosional yang kuat.
Tahapan ketiga disebut sebagai fase tindakan bunuh diri pertama (Erste Suizidhandlungsphase). Individu yang mencapai tahapan ini sudah membulatkan niat untuk bunuh diri. Ironisnya secara tampak luar, individu tampak tenang dan ekspresi emosinya tidak lagi ekstrim seperti di tahapan sebelumnya. Individu tidak lagi ragu, bahwa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar dari masalahnya, hal inilah yang membuatnya tampak lebih tenang. Kondisi ini kerap membuat orang di sekitarnya menganggap ia sudah stabil dan menghentikan penanganan. Bila dilihat dengan lebih teliti, individu di tahap ini lebih sedikit berbicara, jarang atau samasekali tidak menunjukkan kontak mata, atau tidak memiliki rencana secara konkret apa yang akan ia lakukan di beberapa jam atau hari mendatang. Kepekaan staf medis yang menangani individu berperan penting di tahap ini. Individu sebaiknya belum diperbolehkan pulang dari fasilitas penanganan intensif hanya berdasarkan observasi singkat bahwa ia sudah tampak lebih tenang.
Di tahapan keempat, yaitu fase ambivalen akhir (Finale Ambivalenzphase), individu menjalankan rencananya untuk bunuh diri, namun masih terdapat keraguan dalam diri individu. Dalam beberapa kasus misalnya, individu pergi ke stasiun kereta untuk melakukan rencana bunuh diri, namun sengaja menunggu lebih lama sebelum melangkah ke peron kereta. Atau sengaja berjalan bolak-balik di jembatan, di mana ia merencanakan bunuh diri. Peran masyarakat umum yang berada di tempat-tempat, di mana bunuh diri biasanya dilakukan, sangatlah penting. Dari rekaman kamera pengawas di tempat umum dapat diteliti bagaimana postur dan cara bergerak individu yang melakukan bunuh diri di tempat tersebut. Penelitian tentang bunuh diri di jembatan Golden Gate di Amerika Serikat yang dikutip oleh Reich (2012), menunjukkan pelaku bunuh diri di sana kerap terlihat membungkuk ke depan dengan kedua tangan tersilang di dada, postur tubuh sangat tegang dengan tatapan mata mengarah ke bawah. Informasi semacam ini menjadi bahan pelatihan bagi orang yang sering berada di tempat-tempat seperti itu, misalnya polisi, supir taksi, atau masinis kereta api, agar rencana bunuh diri secepatnya dapat dikenali dan dicegah.
Fase tindakan bunuh diri secara final (Finale Handlungsphase) merupakan tahap kelima, di mana individu sudah melakukan tindakan bunuh diri. Kerapkali terdapat jeda waktu antara tindakan bunuh diri dengan berakhirnya nyawa individu. Reaksi cepat masyarakat yang berada di tempat kejadian dapat menjadi harapan untuk menyelamatkan individu yang melakukan tindakan bunuh diri. Masyarakat yang berada di tempat kejadian sebaiknya segera menghubungi rumah sakit terdekat atau nomor darurat 119 untuk meminta bantuan darurat medis dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.
Tahap keenam adalah fase kesadaran diri (Aufwachen), di mana individu menyesali tindakannya untuk bunuh diri. Banyak penyintas bunuh diri, atau orang yang selamat dari tindakan bunuh diri, bahkan menyatakan penyesalan tersebut datang segera setelah tindakan bunuh diri dilakukan. Sayangnya pada beberapa jenis tindakan bunuh diri, tidak ada waktu untuk merasakan penyesalan ini karena kematian datang seketika. Individu yang dapat diselamatkan dari tindakan bunuh diri membutuhkan penanganan medis yang intensif dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat mencetuskan munculnya kembali keinginan untuk bunuh diri. Secara jangka panjang diperlukan pula penanganan medis dan terapi psikologis yang berkelanjutan untuk membantu individu kembali ke kehidupannya dengan kemampuan menyelesaikan masalah dan regulasi emosi yang lebih baik.
Bunuh diri dapat dicegah. Mungkin tidak semua kasus bunuh diri yang kita temui dapat dicegah, namun setiap usaha menjaga kehidupan patut dilakukan karena setiap nyawa adalah berharga.
Referensi:
- Joiner, T. (2005). Why people die by suicide. Harvard University Press.
- Reisch, T. (2012). Wo kann Suizidprävention ansetzen? Vorschlag eines 6-Phasen-Modells suizidaler Krisen, Psychiatrische Praxis, 39: 257-258, http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1305205.